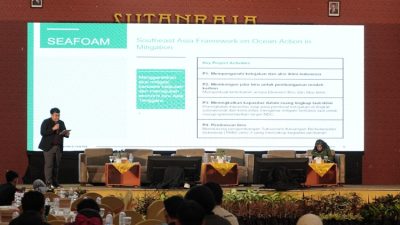Kolase.id – Ocean Program Manager Yayasan EcoNusa Mida Saragih menegaskan agar hukum tidak dimanfaatkan menjadi produk yang malah mendukung eksploitasi alam di Indonesia. Termasuk di sektor perikanan yang merugikan masyarakat adat, tradisional, dan pesisir.
“Saya punya kerisauan, setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu terbit, semua proses perizinan, termasuk di dalamnya sektor kelautan dan perikanan, disederhanakan,” kata Mida dalam salah satu sesi diskusi di acara Green Press Community (GPC) di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Penyederhanaan tersebut, lanjutnya, berpeluang memunculkan ancaman alih fungsi terhadap kawasan konservasi. Misalnya kawasan itu dijadikan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pada kesempatan itu Mida membahas Peraturan Pemerintah (PP) yang muncul sepanjang 2023 ini, yaitu PP No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan PP No. 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
Dalam PP No 26/2023, pemanfaatan hasil sedimentasi didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang membolehkan pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan sedimen di laut. “Praktisnya ini adalah tambang pasir laut,” kata Mida.
Dia lantas mengingatkan apa yang telah terjadi di Pulau Kodingareng, Sulawesi Selatan, yang sempat menjadi kawasan penambangan pasir laut oleh PT Royal Boskalis untuk keperluan pembangunan Makassar New Port (MNP), salah satu proyek strategis nasional. Pengerukan pasir menggunakan kapal Queen of the Netherlands itu berlangsung pada periode Februari hingga Agustus 2020.
“Setelah PT Boskalis tidak lagi beroperasi di Pulau Kodingareng di Sulawesi Selatan, nelayan masih susah mendapatkan ikan karena terumbu karangnya rusak, karena lautnya dikeruk untuk kepentingan penambangan pasir laut,” kata Mida.
Dan kini, sambungnya, setelah tidak beroperasi lebih dari satu tahun, apakah bisa langsung pulih ekosistemnya? “Tidak. Banyak nelayan alih fungsi pekerjaan. Bahkan mereka berpindah dari Sulawesi Selatan ke Ambon karena mereka mendapatkan ikan lebih banyak di Ambon.”
Terkait PP No. 11/2023, Mida mempertanyakan tidak adanya definisi yang jelas dari frasa “penangkapan ikan terukur”. Pun di dalamnya tidak dijelaskan ukuran tonase kapal untuk penggolongan nelayan yang nantinya terkait dengan kuota penangkapan ikan.
Hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan siapa sebenarnya yang berhak menerima manfaat dari peraturan itu.
“Tidak ada sosialisasi yang melibatkan pandangan substansial dari subjek hukum, yakni nelayan. Tidak ada naskah akademik untuk kebijakan penangkapan ikan terukur,” kata Mida.
Selain itu, jika merujuk pada Undang-Undang No. 45/2009 tentang Perikanan, jelas Mida, tidak ada terminologi hukum untuk penangkapan ikan terukur.
“Jadi kami pada level ini merasa bahwa hukum digunakan untuk melegalkan satu upaya guna mendapatkan penghasilan lebih banyak di sektor perikanan,” tegasnya.
EcoNusa juga menyoroti soal privatisasi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang sebenarnya sudah tidak bisa terjadi setelah pada tahun 2011 Mahkamah Konstitusi mengabukan judicial review UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Khususnya, mengenai Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3).
Namun kemudian muncul tiga PP yang menurut Mida, “mengingkari” keputusan hakim MK, yakni PP No. 12/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah; PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan, PP No. 43/2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.
“MK sudah menjelaskan bahwanya konsesi ataupun HP3 atau privatisasi di pesisir dan pulau kecil itu dibatalkan. Karena masyarakat pesisir punya hak hidup, hak untuk melintas, untuk memanfaatkan satu kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tiga PP itu mengingkari semangat dari keputusan hakim MK,” jelasnya.
Ketiga PP tersebut pada akhirnya membuat para nelayan kecil kesulitan untuk melakukan pekerjaan mereka guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena, untuk melaut, mereka harus mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), yang proses pembuatannya amat menguras waktu dan tenaga.
Oleh karena itu, EcoNusa mendesak agar keputusan MK tersebut dibaca kembali sehingga tidak memunculkan privatisasi yang menghilangkan hak masyarakat tradisional yang bersifat turun-menurun dan mengancam penghidupan.
“Kita perlu membaca kembali yurisprudensi hakim, yakni hakim MK yang telah membatalkan pasal privatisasi dan menjamin masyarakat tradisional di pesisir itu punya hak hidup yang lebih baik,” tegas Mida.
Green Press Community merupakan ajang perdana yang diorganisasi oleh Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (The Society of Indonesian Environmental Journalists/SIEJ) guna menghimpun ide dan memantik gerakan bersama untuk melestarikan lingkungan hidup di Indonesia.
Berlangsung sejak Rabu (8/11/2023), GPC menghadirkan berbagai learning session, talk show, dan konferensi yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai kalangan, termasuk pers, organisasi non-pemerintah, dan mahasiswa.*