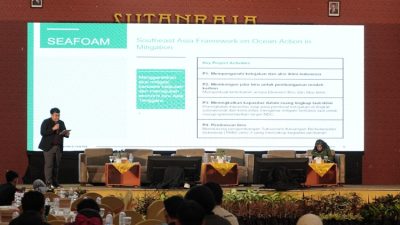Kolase.id – Kota Pontianak masih berjibaku dengan laju produksi sampah yang kian menggunung. Tidak sekadar mencoreng estetika kota, sampah yang menyumbat parit juga dapat memicu bencana banjir.
Pemerintah Kota Pontianak sudah menggulirkan sejumlah kebijakan dan program pengelolaan sampah seperti Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). Kendati demikian, volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Layang masih terus menumpuk.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak melansir, rata-rata sampah yang masuk ke TPA Batu Layang mencapai 400 ton per hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan sampah di tingkat masyarakat masih belum optimal.
Hal ini selaras dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pontianak. “Kami terus berupaya melakukan pembersihan sampah yang mengendap di saluran air,” kata Syafi’i, Staf Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Pontianak.
Ia menyebut sampah yang diangkut dari parit-parit primer di wilayah kota mencapai 30 ton setiap hari. Sampah tersebut tidak hanya berupa plastik, namun juga terdapat sampah domestik (rumah tangga) yang jumlahnya lebih dominan.
“Satu hari dapat mengangkut enam dump truck, satu dump truck bisa lima ton berarti sekitar 30 ton sampah yang diangkut dan berakhir di TPA,” ujar Syafi’i.

Kondisi ini menandakan pentingnya sinergi antara program pengelolaan sampah yang ada dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya. Tanpa keterlibatan aktif semua pihak, persoalan sampah di Kota Pontianak akan semakin kompleks.
Satu di antara permasalahan sampah adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan dan pemilahan sampah. Hal ini mencerminkan pola pikir lama yang melihat sampah sebagai kotoran yang harus dibuang, tanpa mempertimbangkan nilai atau dampaknya.
Namun, di tengah tantangan ini, inisiatif muncul dari Kampung Wisata Caping. Sebuah komunitas di bantaran Sungai Kapuas yang berhasil mendobrak cara pandang sampah menjadi sumber potensi dan inovasi.
Beny Tanheri, pengelola Kampung Wisata Caping adalah sosok di balik transformasi ini. Ia melihat sampah bukan sekadar buangan, melainkan peluang yang belum dimanfaatkan.
“Sampah ini sumber masalah sekaligus potensi untuk menghasilkan barang yang lebih bernilai. Tantangan kita saat ini adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk mengelola ini. Dari mencegah, memilah, hingga mengolah,” ungkapnya.
Inovasi Berbasis Komunitas: Peternakan, Kerajinan, Hingga Hotel
Kampung Caping mengembangkan dua jenis pengolahan limbah, baik sampah organik maupun anorganik. Inisiatif ini menciptakan siklus ekonomi sirkular. Limbah organik diubah menjadi sumber daya bagi peternakan lokal, sementara sampah anorganik, dengan sentuhan inovasi disulap menjadi kerajinan bernilai ekonomi.

“Di Kampung Caping ini kita punya peternakan ayam. Namanya Menteng Farm. Selain sampah dari masyarakat, kami juga kerja sama dengan satu di antara hotel besar di Kota Pontianak yakni Aston Group untuk olah sampah organik menjadi pakan. Hasilnya, peternakan ini bisa menekan biaya pakan hingga 1,5 juta tiap bulannya,” ucapnya.
Arifin, Humas Hotel Aston Pontianak mengatakan, kerja sama ini dilakukan sebagai perpanjangan program Waste Management yang mengharuskan setiap unit hotel untuk mengelola sampah, baik organik maupun anorganik.
“Dari pusat kita ada program Waste Management. Setiap unit hotelnya diminta untuk mengelola sampah, baik yang organik maupun anorganik. Aston Pontianak dengan keterbatasan area, berinisiatif untuk melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah organik karena hampir 70% sampah hotel itu adalah sampah organik,” ungkapnya.
Mengubah sampah organik menjadi pakan merupakan bagian penting dari prinsip hierarki daur ulang pangan. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi dalam menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan, tetapi menawarkan solusi pakan yang ekonomis dan berkelanjutan bagi para peternak. Dengan demikian, limbah pangan bertransformasi menjadi sumber daya yang sangat bernilai.
Pada pengolahan sampah anorganik, plastik-plastik yang telah dikumpulkan dan dipilah diubah menjadi produk-produk cantik dan fungsional berkat sentuhan kreatif tangan masyarakat setempat, di antaranya caping dan tote bag.
“Kami mengolah sampah-sampah anorganik di antaranya dijadikan kerajinan seperti caping dari plastik, hasilnya caping yang dibuat dari plastik juga lebih tahan lama. Selain itu ada juga selimut hotel yang dijadikan sebagai tote bag,” jelas Beny.
Inisiatif kreatif ini tidak hanya mengurangi timbulan sampah anorganik yang sulit terurai, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Dengan mengubah limbah menjadi produk bernilai jual, Kampung Caping menunjukkan bagaimana pendekatan inovatif dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan sekaligus memberdayakan komunitas.
Kampung Caping dan Yuka: Satu Tubuh Beda Wajah
Cerita tentang peradaban sungai di Kampung Caping tak dapat dibandingkan dengan kondisi Kampung Yuka saat ini. Permukiman padat penduduk di Kelurahan Sungai Beliung, Pontianak Barat ini masih harus berjibaku dengan sampah saban hari.
Lurah Sungai Beliung Bastiaruddin tak menampik kepadatan populasi penduduk di Kampung Yuka. “Di sana ada tiga RW (rukun warga) dan 19 RT (rukun tetangga). Di RW 16 ada 7 RT, RW 17 ada 6 RT, dan RW 18 ada 6 RT,” katanya menjawab pesan via WhatsApp, Minggu (27/7/2025).
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II tahun 2024 mencatat, jumlah penduduk di Kelurahan Sungai Beliung mencapai 59.376 jiwa.
Sementara hasil assessment awal Tim Survei Keluarga Pembaharu (Gaharu) Pontianak mencatat ada sekitar 7000 jiwa menghuni Kampung Yuka. Sebuah permukiman yang tak lagi sanggup bernafas lega. Jika dihitung rata-rata, setiap RT dihuni oleh 368 jiwa, angka yang mencerminkan betapa padatnya kampung ini.
Kepadatan tak hanya terasa pada lorong sempit dan rumah-rumah yang berdempetan. Ia juga terasa pada volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Dari sisa makanan, bungkus plastik, botol, popok, hingga limbah rumah tangga lainnya, semuanya mencari jalan keluar. Sayangnya, jalan keluar itu bukan tempat sampah yang terkelola, melainkan parit-parit kecil dan saluran air di sekitar permukiman.
Parit-parit yang dulunya mengalir jernih dan menjadi saluran resapan, kini berubah menjadi selokan hitam yang mengalir malas, tersumbat oleh sampah plastik dan endapan limbah. Saat hujan turun, air tak lagi mengalir, melainkan meluap, masuk ke rumah-rumah, membawa bau busuk dan potensi penyakit.
Sungai yang menjadi hilir dari semua itu hanya bisa pasrah. Ia menerima semua yang dibuang dari RT ke RT, dari RW ke RW, tanpa ampun. Volume sampah yang terbawa menuju sungai meningkat drastis dan bukan karena perilaku satu dua orang semata, tetapi karena sistem pengelolaan sampah yang tidak sanggup mengikuti laju pertumbuhan penduduk.
Beranjak dari fenomena tersebut, tampak jelas krisis lingkungan mendesak untuk ditangani. Ada realitas pahit kehidupan di bantaran sungai Kampung Yuka. Tumpukan sampah plastik dan organik memenuhi area kolong rumah-rumah panggung yang seharusnya menjadi ekosistem penting bagi biota sungai.

Perahu-perahu kecil yang sejatinya menjadi simbol peradaban sungai, justru terjebak dalam lumpur dan limbah. Sungai yang dulunya menjadi jalur transportasi dan sumber penghidupan, kini perlahan berubah menjadi tempat pembuangan sampah terbuka.
Hal ini memperlihatkan kurangnya sistem pengelolaan sampah yang memadai, minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan DAS.
Demikian halnya dengan persoalan pasar, ruang pertemuan ekonomi, sosial, dan budaya. Ketika pasar tidak tertata dengan baik, ruang ini bisa berubah menjadi sumber polusi yang sistemik. Apalagi di daerah aliran sungai, apa yang dibuang hari ini, bisa menjadi ancaman bagi ekosistem sungai esok hari.
Pasar menjadi denyut ekonomi penting, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga dan pedagang kecil. Namun, di saat bersamaan, kurangnya fasilitas pengelolaan limbah pasar membuat kawasan ini menyumbang signifikan terhadap pencemaran lingkungan. Sampah plastik dari bungkus makanan, kantong belanja, dan sisa bahan makanan sering kali langsung dibuang ke sungai atau kanal terdekat, yang kemudian mengalir ke laut.
Melihat kondisi di Kampung Yuka, potensi untuk bertransformasi sesungguhnya sangat besar. Satu di antaranya karena ada area pasar yang selalu memproduksi sampah organik. Hal ini memberikan potensi pemanfaatan larva Black Soldier Fly (BSF) atau yang lebih dikenal dengan maggot.
Teknologi Ramah Lingkungan: Maggot dan Biopond
Beny Tanheri yang juga seorang pegiat lingkungan ini telah berhasil mengembangkan budidaya maggot BSF. Menurutnya, maggot memiliki kemampuan luar biasa dalam mengonsumsi dan mengurai limbah organik.
Beny menjelaskan, dalam kondisi ideal, satu kilogram maggot mampu mengonsumsi hingga lima kilogram limbah organik per hari. Bahkan bisa lebih tergantung pada jenis dan kelembapan limbah. Kecepatan konsumsi ini menjadikan maggot sebagai agen dekomposer yang sangat efisien dalam mengurangi volume sampah organik.
Di tengah krisis sampah organik yang melanda kawasan di bantaran sungai, siapa sangka larva kecil seperti maggot bisa menjadi pahlawan ekologi. Hal ini dapat dilihat pada aktivitas maggot dalam sebuah biopond atau tempat penguraian limbah organik secara alami dan ramah lingkungan. Sampah dapur seperti sisa sayur, buah, dan daun yang biasanya menjadi limbah yang mencemari perairan, kini justru diolah menjadi sumber kehidupan baru.

Biopond ini bukan hanya tempat pembusukan, tetapi tempat transformasi. Dalam waktu singkat, maggot mampu mengurai sampah organik dengan efisien. Mereka mengonsumsi limbah dan mengubahnya menjadi biomassa bernutrisi tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak atau ikan. Hasil akhirnya? Sisa organik yang sudah terurai dan lebih ramah bagi tanah, serta pengurangan drastis jumlah sampah yang berpotensi mencemari lingkungan.
Dalam sistem ini, kata Beny, satu unit biopond mampu menampung sekitar 5 kilogram maggot hidup. Apabila digunakan secara kolektif, delapan unit biopond dapat melayani kebutuhan pengolahan limbah organik dari sekitar 500 rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa teknologi sederhana ini sangat potensial untuk diterapkan di tingkat komunitas dalam skema pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Hasil samping dari budidaya maggot juga memiliki nilai tambah. Kasgot atau kotoran maggot, mengandung nutrisi tinggi dan dapat langsung dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Selain itu, cangkang eksoskeleton dari maggot yang telah bermetamorfosis juga dapat dijadikan bahan pupuk alami, menjadikan sistem ini hampir tanpa limbah.
Solusi Tambahan: Biopori untuk Rumah Tangga
Selain menggunakan maggot, masyarakat juga dapat membuat biopori yang menjadi solusi lain dalam mengolah limbah organik. Teknologi lubang resapan biopori juga memiliki kontribusi signifikan dalam pengelolaan lingkungan.
Fungsi utama biopori adalah untuk meningkatkan daya serap air tanah, sehingga mengurangi risiko banjir dan genangan. Fungsi tambahan biopori adalah tempat pembuangan limbah organik rumah tangga yang akan terdekomposisi menjadi kompos secara alami.
Setiap metode pengelolaan limbah organik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karenanya, masyarakat bebas memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi lokal dan ketersediaan sumber dayanya.
Muara dari semua pendekatan ini adalah upaya aktif dalam mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA), demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.*