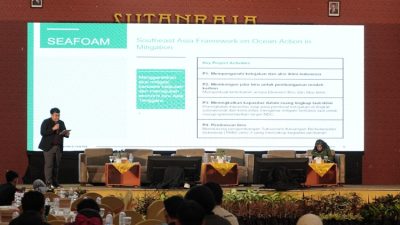Kolase.id – Sejumlah pihak menyoroti urgensi dan efektivitas pembentukan Undang-Undang Masyarakat Adat di tengah tumpang tindih regulasi dan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Perwakilan Koalisi Kawal RUU MA Siti Rakhma Mary Herwati mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 25 undang-undang yang memuat frasa terkait masyarakat adat, 12 hak bawaan yang diatur, serta 8 undang-undang dan 15 peraturan pelaksanaan yang mengatur prosedur pengakuan.
Selain itu, ada tujuh kementerian atau lembaga di tingkat pusat yang memiliki kewenangan terkait masyarakat adat. Namun, menurut Siti, isi regulasi antar-lembaga kerap tidak sinkron sehingga menimbulkan sektoralisme hukum.
“Banyak undang-undang justru bertentangan dengan hak masyarakat adat, tidak memberikan perlindungan maupun pengakuan terhadap wilayah adat,” ujarnya menjawab pertanyaan dari Kolase.id saat menjadi narasumber pada media briefing Mendukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat di Pontianak, Jumat (8/8/2025).
Siti menekankan bahwa efektivitas Undang-Undang Masyarakat Adat tidak hanya ditentukan oleh substansinya, tetapi juga oleh pelaksanaan di lapangan. Faktor seperti kesiapan aparat hukum, struktur kelembagaan, dan dukungan peraturan turunan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi.
Ia mencontohkan perdebatan metode penyusunan yang kemudian apakah mengikuti pola omnibus law seperti UU Cipta Kerja atau cara konvensional yang masih belum tuntas.
Koalisi mencatat bahwa di lapangan, masyarakat adat masih menghadapi konflik agraria yang mencakup ribuan hektare wilayah adat, kriminalisasi, serta kerusakan lingkungan.
Sepanjang sepuluh tahun terakhir, sekitar 1.000 orang masyarakat adat ditangkap, atau rata-rata 100 orang per tahun, akibat mempertahankan wilayahnya yang kerap diterbitkan izin HGU, HTI, pertambangan, maupun infrastruktur. Dampak terparah dirasakan perempuan dan anak, termasuk hilangnya pengetahuan tradisional dan kebebasan mengelola wilayah adat.
“Kami mendesak pemerintah menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi dan mengakui masyarakat adat,” tegas Siti.
Menurutnya, pengakuan dan perlindungan ini adalah hal sentral untuk mencegah penderitaan berkepanjangan akibat kebijakan yang berpihak pada korporasi.
Menanggapi hal tersebut Akademisi Universitas Tanjungpura Salfius Seko juga menilai bahwa undang-undang sektoral yang ada saat ini belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat adat.
Menurutnya, setidaknya terdapat 25 undang-undang yang memuat ketentuan mengenai masyarakat adat, namun regulasi tersebut bersifat parsial dan tidak menuntaskan permasalahan.
“Karena itu, perlu undang-undang tersendiri yang komprehensif, yang tidak hanya bicara soal hak, tapi juga pemenuhan hak ekosob (ekonomi, sosial, budaya) dan hak sipol (sipil dan politik),” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemenuhan kedua jenis hak tersebut merupakan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk masyarakat adat. Perlindungan tersebut, lanjutnya, tidak boleh berhenti pada pengakuan semata, tetapi juga mencakup pemenuhan hak secara nyata.
Menanggapi pertanyaan terkait efektivitas, akademisi tersebut sependapat dengan pandangan koalisi bahwa keberhasilan UU Masyarakat Adat tidak dapat diukur hanya dari keberadaannya.
“Pertanyaannya adalah setelah ada undang-undangnya, apa langkah berikutnya? Bagaimana pelaksanaannya, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana perlindungannya, dan bagaimana penyelesaian sengketanya,” jelasnya.
Ia mencontohkan pengalaman di Kalimantan Barat, di mana dari 14 kabupaten/kota, delapan daerah telaakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Namun, persoalan masih terjadi meski peta tersebut sudah ada.
“Faktanya, tidak semua masalah terselesaikan. Artinya, efektivitas hanya bisa diukur dari hasil akhir, bukan dari proses awal pembentukan regulasi,” tegasnya.
Menurutnya, pembahasan efektivitas UU Masyarakat Adat harus disertai kajian mendalam, termasuk mengidentifikasi kekurangan dan hambatan implementasi. Dengan demikian, undang-undang tersebut benar-benar menjadi instrumen perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat, bukan sekadar simbol pengakuan.*